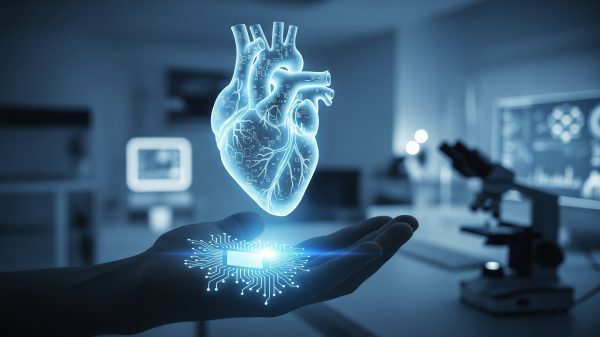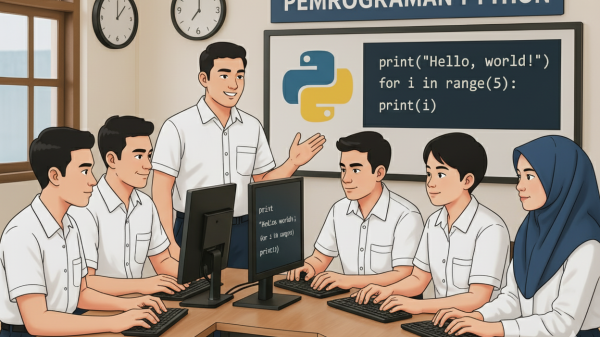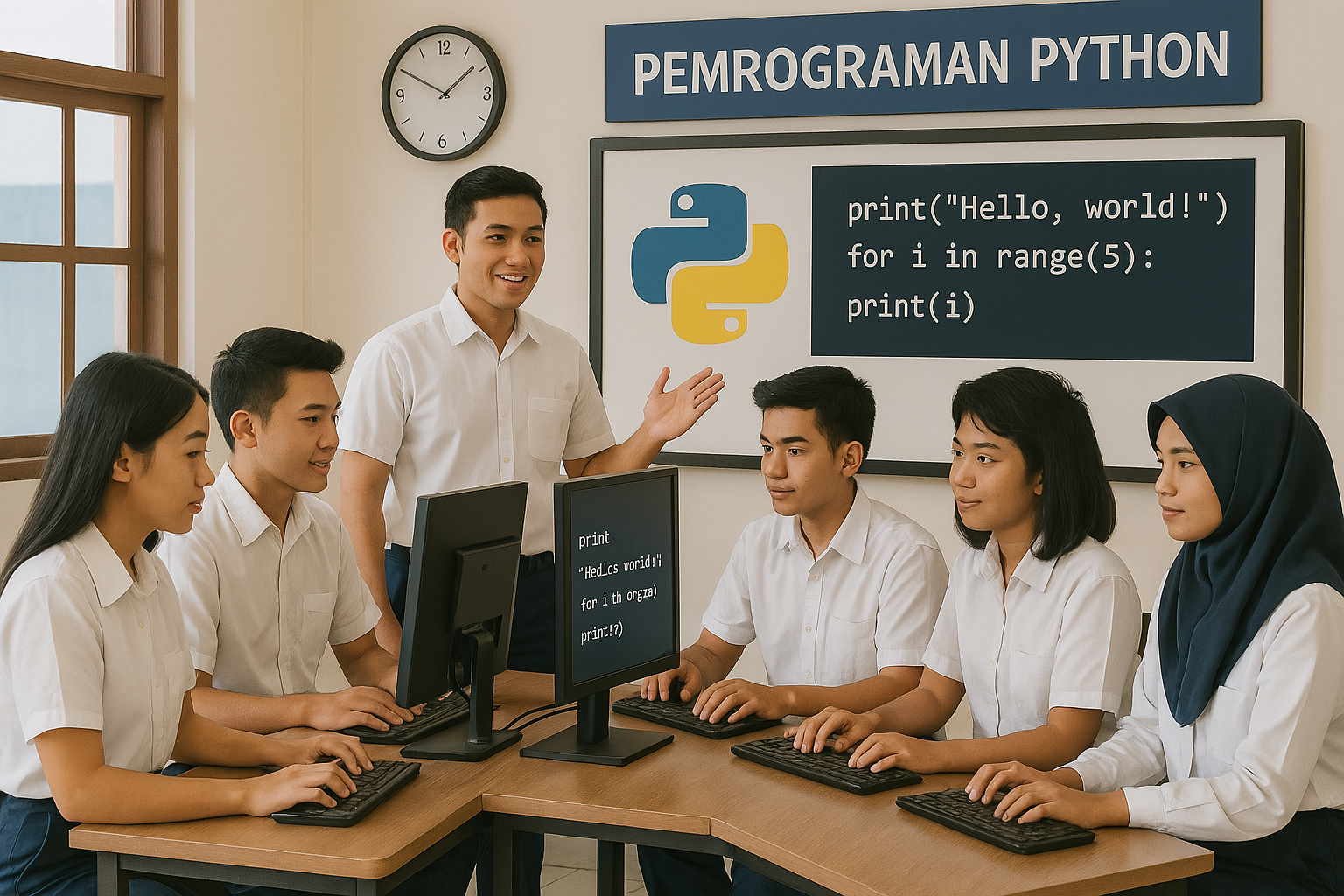- Kecerdasan Artifisial generatif telah masuk ke ruang kelas.
- Literasi dan etika menjadi faktor penentu apakah KA memperkuat atau merusak proses belajar.
- Penelitian terkini menunjukkan kebutuhan mendesak akan pendidikan literasi Kecerdasan Artifisial di tingkat menengah.
Tidak dipungkiri banyak tugas sekolah dikerjakan dengan bantuan Kecerdasan Artifisial, Misalkan untuk membuat teks pidato. Jika kita berikan tugas ini pada KA maka ia akan segera menyodorkan teks pidato lengkap, rapi, dan persuasif. Coba bandingkan bila dikerjakan murid tanpa bantuan KA. Dengan bantuan KA dalam waktu kurang dari dua menit, tugas yang biasanya membutuhkan satu jam selesai sudah.
Luaran yang diberikan oleh Kecerdasan Artifisial semakin berkualitas. Bahkan untuk tugas-tugas yang lebih kompleks. Semakin hari semakin akurat dan efisien. Membuat guru harus berpikir panjang untuk membuat soal atau tugas.
Situasi seperti ini bukan lagi pengecualian, melainkan menjadi bagian dari realitas baru di dunia pendidikan Indonesia dan dunia. Teknologi Kecerdasan Artifisial generatif seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini telah masuk ke ruang-ruang belajar tanpa mengetuk pintu. Mereka membantu, sekaligus menantang, cara siswa belajar dan guru mengajar.
Namun di balik kemudahan itu, muncul pertanyaan mendasar: apakah siswa memahami apa yang mereka gunakan? Apakah mereka bisa membedakan antara bantuan dan ketergantungan? Di sinilah isu literasi Kecerdasan Artifisial dan kesadaran etis menjadi penting, bahkan krusial.
Riset-riset terbaru dari jurnal internasional mengungkap wajah lain dari euforia Kecerdasan Artifisial dalam pendidikan. Sebuah studi sistematis yang dilakukan oleh Ogunleye dan rekan-rekannya (2024) menunjukkan bahwa Kecerdasan Artifisial generatif telah banyak digunakan dalam proses pembelajaran dari membuat soal latihan hingga menjadi tutor virtual. Tapi manfaat itu hanya muncul jika pengguna memahami cara kerja dan batasan teknologi tersebut.
Sementara itu, Gu dan Ericson (2025) dalam ulasan integratifnya menyoroti bahwa tingkat literasi Kecerdasan Artifisial di kalangan pelajar, khususnya siswa SMA dan guru mereka, masih tergolong rendah. Kebanyakan hanya tahu “cara pakai”, tanpa paham konteks, risiko, atau etika penggunaannya. Mereka menyebut ini sebagai “kesenjangan literasi Kecerdasan Artifisial” yang berpotensi memperlebar jurang antara siswa yang siap menghadapi masa depan dan yang hanya mengikuti arus.
Bahaya lain mengintai dari penggunaan Kecerdasan Artifisial yang tanpa panduan: plagiarisme dan kemalasan intelektual. Penelitian oleh Ateeq dkk. (2024) mencatat bahwa penggunaan Kecerdasan Artifisial untuk menyelesaikan tugas tanpa pengakuan sumber telah menjadi praktik yang cukup lazim. Banyak siswa bahkan menganggapnya bukan sebagai pelanggaran, melainkan sebagai bagian dari efisiensi belajar.
Namun, sisi lain dari Kecerdasan Artifisial juga mulai terlihat. Studi Mallillin (2024) menunjukkan bahwa ketika digunakan dengan terarah, Kecerdasan Artifisial justru meningkatkan motivasi belajar dan hasil akademik siswa. Siswa yang terbiasa berdialog dengan Kecerdasan Artifisial untuk memahami konsep pelajaran cenderung lebih percaya diri dan mandiri. Ini menunjukkan bahwa Kecerdasan Artifisial bukanlah masalah, melainkan alat dan seperti alat lainnya, ia bisa berguna atau berbahaya tergantung tangan yang menggunakannya.
Sayangnya, mayoritas studi yang ada masih terfokus pada mahasiswa dan pendidikan tinggi. Padahal, revolusi Kecerdasan Artifisial saat ini telah menjangkau siswa SMA bahkan SMP. Di Indonesia sendiri, belum banyak penelitian empiris yang mengungkap bagaimana literasi Kecerdasan Artifisial dan pemahaman etis mempengaruhi kinerja belajar siswa di tingkat sekolah menengah.
Inilah yang membuat munculnya usulan penelitian seperti “Pengaruh Literasi Kecerdasan Artifisial dan Kesadaran Etis terhadap Kinerja Akademik Siswa SMA di Era Kecerdasan Artifisial Generatif” menjadi penting dan mendesak. Penelitian seperti ini bisa membuka pemahaman baru tentang bagaimana siswa benar-benar menggunakan Kecerdasan Artifisial bukan hanya sebagai alat bantu teknis, tetapi sebagai ruang interaksi kognitif dan moral.
Lebih dari sekadar tahu cara pakai, literasi Kecerdasan Artifisial harus mencakup pemahaman tentang bias algoritma, akurasi informasi, hingga cara memverifikasi data yang dihasilkan. Di sisi lain, kesadaran etis menyangkut sikap terhadap orisinalitas, penghargaan terhadap karya sendiri, serta tanggung jawab dalam belajar. Dua hal ini jika digabungkan, menjadi dasar penting bagi pendidikan abad ke-21.
Maka, sekolah perlu bergerak lebih cepat. Kurikulum literasi digital perlu diperluas menjadi literasi Kecerdasan Artifisial. Guru perlu mendapatkan pelatihan bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga untuk memfasilitasi penggunaan Kecerdasan Artifisial secara bijak. Dan siswa sebagai pengguna paling aktif perlu dilatih agar tidak sekadar menjadi peniru cerdas, tetapi pemikir kritis yang mampu berdialog dengan teknologi.
Teknologi Kecerdasan Artifisial memang menjanjikan efisiensi dan kemudahan, tetapi tanpa literasi dan kesadaran, ia bisa menjadi alat pelumpuh berpikir. Maka, jika kita ingin menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga kuat secara moral, pendidikan literasi Kecerdasan Artifisial harus menjadi prioritas, bukan sekadar pilihan.